Abstrak
Tidak semua narasi menciptakan makna, atau menciptakan jenis makna yang sama; sebaliknya, beberapa cerita memperkuat ketidakbermaknaan, yang—menurut pendapat mereka—merupakan bentuk pembuatan makna tersendiri. Artikel ini meneliti bagaimana makna dirumuskan melalui narasi tanpa adanya kematian yang bermakna, khususnya dalam konteks pembunuhan tanpa motif. Kunci untuk menghasilkan narasi yang bermakna tentang fakta yang diperebutkan adalah keterampilan pencerita dalam mengontekstualisasikannya. Dengan menanyakan bagaimana makna dirumuskan tanpa adanya kematian yang bermakna, saya merenungkan ketidaksesuaian mendasar antara kebutuhan naratif aktor hukum dan nonhukum setelah pembunuhan. Penelitian ini melibatkan pengalaman saya setelah pembunuhan bibi saya pada Malam Tahun Baru, 2019. Saya meneliti pekerjaan naratif yang sedang berlangsung dari keluarga saya di seluruh persiapan pemakaman dan drama ruang sidang. Ruang sidang menyajikan contoh konkret dari proses entekstualisasi yang berbeda antara narasi aktor hukum dan nonhukum dan menunjukkan bagaimana perbedaan ini memberikan berbagai jenis makna pada peristiwa. Dengan memanfaatkan teknik analisis naratif, saya menganalisis ekspresi kehilangan keluarga saya untuk memahami cara rumit yang dilakukan para korban untuk mengartikulasikan kembali makna dalam hidup mereka.
BAGIAN I: RUMAH

Kenangan-kenangan tentang saat-saat pembunuhan bibi saya ini berbicara, dengan cara yang tak terduga, pada amandemen Marx terhadap saran Hegel bahwa peristiwa-peristiwa sejarah dunia terjadi dua kali. Pertama kali, tulisnya, peristiwa-peristiwa itu muncul sebagai tragedi, dan kedua kalinya sebagai lelucon (Marx, 1978 , hlm. 594). Artikel ini mencatat pengalaman-pengalaman keluarga saya dalam dua konteks utama: segera setelah pembunuhan bibi saya dalam suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kedua selama pengalaman yang terkadang menggelikan dari persidangan terdakwa. Sementara sejumlah cendekiawan telah menganalisis proyek-proyek pembuatan makna dari narasi-narasi traumatis, klaim saya berbeda. Saya meneliti bagaimana dalam keadaan-keadaan ekstrem keinginan untuk memberi perintah pada peristiwa-peristiwa eksternal dapat digagalkan atau ditentang. Korban-korban bersama mungkin menolak untuk memahami pembunuhan atau menolak untuk menerapkan koherensi karena hal itu menerapkan logika atau rasa rasionalitas tertentu pada peristiwa tersebut, padahal justru rasa irasionalitaslah yang lebih disukai untuk dikembangkan. Dengan kata lain, beberapa narasi semakin memproyeksikan ketidakbermaknaan. Keteraturan peristiwa dalam narasi yang dihaluskan menyamarkan ketidakkonsistenan realitas yang dialami, dan dalam artikel ini, saya menganalisis proyek narasi “korban bersama”: keluarga yang berduka atas mereka yang terbunuh. 2
Narasi dapat dideskripsikan sebagai penggunaan sistem simbolik untuk membangun koherensi temporal dan logis di seluruh pengalaman masa lalu, masa kini, dan yang belum terwujud (Kermode, 1968 , hlm. 35–36; Prince, 2020 ). Karena itu, Kleinman dan Seeman ( 2000 ) telah mempelajari narasi sebagai bentuk penalaran kritis yang membentuk dan mendefinisikan konsepsi tentang diri. Cerita memodelkan dunia, memperoleh atau menyulap sebuah struktur untuknya. Cerita adalah klaim untuk mengetahui masa lalu, dan dengan perluasan untuk memahami masa kini dan masa depan—karena kita memperluas pengetahuan kita tentang masa lalu sebagai hipotesis tentang peristiwa masa depan.
Kata-kata ayah saya di atas menunjukkan apa yang Marie Louise Pratt ( 1977 , hlm. 148) sebut sebagai “teks tampilan” lisan. Teks itu koheren, menarik, dan terstruktur. Teks itu penuh dengan elemen-elemen yang diidentifikasi oleh Labov dan Waletzky ( 1967 ) sebagai karakteristik narasi yang matang: abstrak, orientasi, tindakan yang rumit, evaluasi, resolusi, dan koda yang mengembalikan pendengar ke bentuk sekarang. Namun, teks tampilan ini jarang muncul dalam bentuk yang lengkap. Di sini, saya meneliti narasi yang sedang berkembang yang masih rentan terhadap perubahan keadaan. Ada banyak literatur yang membahas tentang narasi pengalaman sulit, yang sering kali menganut pandangan yang diimpor dari psikologi klinis bahwa karya naratif bersifat terapeutik, bahwa narasi menyembuhkan (Becker, 1997 ; Divinsky, 2007 ; Kirmayer, 1992 ; Kleinman, 1988 ; Mattingly, 1998 ; Young, 1976 ). 3
Dalam narasi penyakit, pengalaman tubuh menjadi terlihat. Dibuat terlihat, mereka menjadi dapat dijelaskan, menggemakan contoh yang diberikan oleh Claude Lévi-Strauss dalam Antropologi Struktural ( 1977 ), di mana diagnosis seorang dukun menghubungkan penyakit seorang individu dengan bahasa budaya mitologi. Dengan melakukan hal itu, “[dukun] menyediakan wanita yang sakit dengan bahasa …. Dan itu adalah transisi ke ekspresi verbal ini—pada saat yang sama memungkinkan untuk menjalani dalam bentuk yang teratur dan dapat dipahami sebuah pengalaman nyata yang kalau tidak akan menjadi kacau dan tidak dapat diungkapkan—yang mendorong pelepasan proses fisiologis….” (Lévi-Strauss 1977 , hlm. 198) Pandangan ini dapat dimengerti menanggapi apa yang dihadirkan dalam ucapan tetapi mengabaikan apa yang tidak—dan seperti yang akan saya tunjukkan, penghilangan naratif sering kali sama pentingnya dengan apa yang diceritakan.
Peristiwa seperti pembunuhan dapat diartikulasikan pada skala inklusivitas dan eksklusivitas yang berbeda. Ada banyak cara di mana pembunuhan tidak masuk akal. Pada skala “kecil”—peristiwa pembunuhan—ketiadaan makna muncul dari ketiadaan motif yang jelas. Pada skala yang relatif “lebih besar”, pembunuhan dapat diartikulasikan melalui berbagai narasi termasuk narasi yang merendahkan martabat (“ini hanya menunjukkan bagaimana tidak ada lagi rasa hormat terhadap hukum”) dan narasi yang menyelamatkan (“dia berada di tempat yang lebih baik sekarang, dan dia akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan untuk apa yang dia lakukan”). Ketiadaan membingkai kehadiran naratif. Ketika peneliti bertanya: Apa yang terjadi? Kita menerima narasi yang dipisahkan dari konteks yang memunculkan penceritaan kisah itu dengan cara itu pada saat itu . Akibatnya, kita diberi sedikit pemahaman tentang keadaan politik dan pribadi yang kompleks yang memunculkan kisah-kisah kita yang paling sulit dan serius. 4
Pendekatan saya di sini terhadap narasi semacam itu ada dua. Pertama, saya bertanya bagaimana keluarga saya membangun rasa makna di tengah krisis, ketika “makna” tampak paling misterius. Saya mengeksplorasi pembuatan makna ini melalui narasi saya sendiri dan narasi keluarga saya. Saya kemudian mengangkat masalah “tidak dapat diungkapkan” dari sudut pandang berikut: Jika karya naratif adalah pemaksaan struktur pada aliran kehidupan yang tidak terstruktur, lalu apa yang tersisa dari konstruksi ini? Paradoks konstruksi makna adalah bahwa ia menyiratkan biner. Apa yang membuat “akal sehat” hanya melakukannya karena ia bertentangan dengan apa yang ” tidak masuk akal .” Dan apa yang tidak masuk akal dapat menjadi “tidak dapat diungkapkan” karena menolak konvensi naratif tentang kausalitas. Mungkin terlalu rumit, terlalu ambigu, atau terlalu keras . Rincian seperti itu mengganggu apa yang disebut lingkaran hermeneutik naratif: rincian harus menambah keseluruhan, dan keseluruhan mencerminkan rincian (Bruner, 1998 , hlm. 20).
Teknik analisis naratif yang saya gunakan sebagian besar diambil dari karya komprehensif Labov ( 2013 ), Labov dan Waletzky ( 1967 ), dan Ochs dan Capps ( 2001 ). Saya mendapat inspirasi dari Ochs dan Capps dalam upaya untuk melampaui analisis teks yang terisolasi untuk mempelajari proyek naratif dan signifikansinya terhadap kehidupan individu yang mengalami trauma. Proyek-proyek tersebut merupakan proyek karena merupakan proses — proyek -proyek tersebut merupakan naratifisasi, bukan narasi.
Pengetahuan naratif
Saya melihat bibi saya Angela di rumah duka. Sarung tangannya menyembunyikan tangan yang terluka. Syalnya ditarik ke atas lehernya. Direktur pemakaman memperingatkan kami bahwa ada tanda-tanda kekerasan yang tidak bisa dia samarkan. Mata memar dan luka tipis di pipi dan bibirnya yang pucat. Penampilan tubuh seseorang terkait erat dengan identitas individu. Itu adalah tanda idiomatik ekspresi pribadi (Goffman, 1963 ). Kecacatannya, tulis Daniel Martin ( 2010 , hlm. 25), “meninggalkan para penyintas almarhum dalam situasi yang meresahkan untuk mengidentifikasi dengan objek yang mengerikan atau menjijikkan yang hanya berisi sisa-sisa identitas lama yang diketahui.” Tubuh menjadi indeks pembunuhannya sendiri, yang mewakili, seperti yang ditunjukkan Amoozegar ( 2024 , hlm. 9), hubungan kompleks antara diri sebelumnya dan tindakan kekerasan yang dilakukannya. Kesulitan memisahkan orang yang Anda kenal dari keadaan kematiannya bertambah besar karena sumber utama identitas mereka menjadi cerminan kematian mereka yang tragis.
Kesulitan yang terlibat dalam menyusun narasi yang menjelaskan trauma yang rumit adalah bahwa narasi tersebut harus bersaing dengan cerita yang diceritakan oleh orang lain, seperti media, penyidik polisi, atau pembela. Narasi-narasi tersebut terlibat dalam politik representasi tentang dunia. Meskipun bersifat politis, narasi-narasi ini jarang eksklusif satu sama lain, melainkan memberlakukan dialog antara para aktor, brikoleur dengan kepentingan yang sangat berbeda, dan menyimpan informasi yang darinya identitas korban direkonstruksi.
Mengacu pada wawancara yang dilakukan dengan orangtua anak-anak yang dibunuh, Martin ( 2010 , hlm. 22) menggambarkan investigasi polisi sebagai “arkeologi” identitas. Hal ini sekaligus bersifat intrusif-ekstraktif, dan mengungkap: mampu mengungkap informasi yang berharga. “Pemindahan korban dan barang-barang fisiknya secara hukum dan fisik dilakukan kepada negara” untuk dianalisis (Martin, 2010 , hlm. 21). Tentu saja, pejabat hukum menganggap signifikansi naratif dan profil karakter pada barang-barang ini (Wigmore 1983 , hlm. 15–19).
Luka menawarkan makna potensial bagi pengamat: jenis kekerasan apa yang dilakukan, intensitasnya, dan apakah kekerasan itu timbal balik, misalnya. Demikian pula, para korban bersama melekatkan makna naratif pada objek yang mereka kaitkan dengan almarhum. Martin ( 2010 , hlm. 37) menggunakan istilah “virtual reselfing” untuk menggambarkan proses ini. Yang lain telah menggunakan istilah “rehumanisasi” untuk menunjukkan pemulangan identitas almarhum dari ranah hukum dan pidana (Corrias, 2016 ; Kwakman et al., 2024 ). Saya memadukan kedua pengertian ini dengan istilah “karakterisasi” untuk menggambarkan suatu bentuk karya naratif yang melibatkan pembuatan penilaian tentang representasi almarhum, sering kali dengan melampirkan makna asosiatif pada berbagai objek. Makna dari suatu item pakaian atau perhiasan, karya seni di dinding, atau halaman dalam buku harian orang yang dicintai dibaca sebagai bermakna karena mereka diposisikan sebagai tanda dalam kompleks perasaan, pikiran, dan penceritaan. Tidak statis, mereka malah terlibat dalam pola evaluasi, yang mampu mengenang “diri yang tidak lagi mampu berkolaborasi dalam penandaannya sendiri” (Martin, 2010 , hlm. 37). Sebagai bentuk entekstualisasi, karakterisasi (atau rekarakterisasi ) melibatkan pelepasan subjek tertentu dari konteks aslinya, untuk menanamkannya kembali dalam wacana baru. Kita mendekontekstualisasikan untuk melakukan rekontekstualisasi (Silverstein & Urban, 1996 ). Representasi pertama-tama membutuhkan reduksi. Untuk mengkarakterisasi , kita membangun kesinambungan identitas yang bergantung pada semiosis pilihan representasional . Snow dan Anderson ( 1987 ) mendeskripsikan proses ini sebagai “penceritaan fiktif,” menafsirkan aspek-aspek kehidupan korban secara retrospektif untuk memberlakukan agensi yang mengakui keadaan kematian mereka. Dengan melakukan itu, kita terlibat dalam bentuk kerja identitas emansipatoris, menolak reduksi hukum Ange ke statusnya sebagai “almarhum.” Dalam memberi “kehidupan” kepada orang mati, kita menolak reduksinya menjadi indeks pembunuhan, menjadi perantara atas nama diri yang tidak mampu berkontribusi pada maknanya sendiri, dan dengan demikian menegaskan klaim untuk mengetahui orang yang meninggal, dan untuk mengetahui mereka dari gudang informasi pribadi. Melalui karakterisasi, kita menampilkan diri kita sebagai orang yang memiliki akses ke badan pengetahuan ahli yang sebanding tetapi berbeda dari keahlian profesional forensik atau hukum. Seperti yang dikatakan ibu saya

Dia menempatkan narasinya sendiri di atas narasi pembelaan, menggabungkan pembenaran terdakwa atas tindakan Ange sebagai bukti keahliannya sendiri. Di sini, kualitas meyakinkan dari karakterisasinya bergantung pada konsistensinya dari waktu ke waktu, dan dalam pengertian ini, karakterisasi pada dasarnya bersifat evaluatif, tergantung pada pengetahuan abadi tentang yang dicirikan, sejauh itu memungkinkan seseorang untuk mengenali contoh-contoh ketika seseorang “dalam” karakter atau bertindak “di luar” karakter. Karena itu, kita dibiarkan dengan satu dari dua reaksi: mempercayai apa yang diberitahukan kepada kita (“itu terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan Ange”) atau kita skeptis (“dia tidak akan pernah melakukan itu”). Dalam pengertian ini, kualitas evaluatif dari karakterisasi terkait dengan tekstualitasnya. Kita membuat penilaian tentang bagaimana seseorang mungkin atau mungkin tidak bertindak berdasarkan rekontekstualisasi karakter itu dalam keadaan hipotetis.
Dengan cara ini, karakterisasi memberikan kemungkinan untuk menceritakan narasi tandingan atau menciptakan cerita yang sesuai dengan dan melawan narasi yang diceritakan di ruang sidang. Legitimasinya berasal dari keterlibatannya dengan narasi hukum, tetapi maknanya berada di luar narasi tersebut. Sebagian, nilai narasi paralel ini terletak pada kualitas korektifnya—dalam meluruskan catatan. Hal ini sendiri tidak memiliki efek yang diperlukan pada pembuatan makna. Jika ada, pendalaman narasi dan karakterisasi ruang sidang mengganggu tatanan berbagai hal. Narasi yang dibangun oleh pengacara sering kali tidak memuaskan karena realitas yang mereka gambarkan jauh lebih padat, dan taruhannya sangat tinggi. Oleh karena itu, korektif cenderung menjauh dari argumen sebab dan akibat yang disamarkan dengan rapi. Jika realitas kurang masuk akal, ia tetap berbagi pengalaman yang tidak masuk akal, membingungkan, dan ambigu dari korban bersama. Di tempat ini, narasi yang bermakna adalah narasi yang berbicara tentang pengalaman mereka. Narasi membangkitkan kebutuhan; konturnya menggambarkan navigasi pengalaman sang pencerita.
Dengan demikian, ada waktu dan tempat untuk narasi tertentu. Menceritakannya di luar batasan tersebut berisiko menimbulkan kesalahpahaman (Frank, 1995 ). Mungkin, ini tampak intuitif bagi pembaca; pepatah bahwa beberapa topik tidak cocok untuk pergaulan yang sopan muncul dalam pikiran. Namun, bagaimana dengan hal-hal yang terlalu sulit untuk dibicarakan di pergaulan informal —di antara kerabat yang pengalamannya sama dengan Anda? Apa artinya bagi suatu subjek yang tidak terucapkan, tidak dapat diucapkan , seperti itu?
Selain ringkasan fakta saat pertama kali menerimanya, kami tidak pernah membicarakan luka-luka Ange. Berkutat pada cara kematian tidak akan menghasilkan apa-apa. Meskipun menempati sudut hati nurani saya yang sangat sulit, narasi yang diindeks oleh luka-lukanya tetap tidak dapat diceritakan. Demikian pula, meskipun telah mengenal pembunuh Ange dan telah menghabiskan hari-hari sebelumnya bersamanya, keluarga saya jarang menyebut namanya sejak saat itu. Itu berdiri sebagai tanda jalan titik engsel antara dialog bersama dengan pengadilan dan keputusan untuk menghilangkannya dari “teks” kami sendiri. Keheningannya tidak mengubah fakta, hanya hubungan kami dengannya, dan dalam perubahan halus itu mengomunikasikan aspek proyek pembuatan makna yang sedang berlangsung.
Dua kenangan yang mencolok menggambarkan hal tersebut. Yang pertama terjadi seminggu sebelum pemakaman. Seorang sepupu jauh duduk bersama orang tua saya dan saya di ruang tamu kami. Ibu menceritakan kisah tersebut, yang terbatas seperti pada tahun sebelum sidang pengadilan: kisah yang kurang detail dan lebih banyak mengungkapkan pengalaman individu saat pemberitahuan kematian. Ia menjelaskan keadaan normal kunjungan orang tua saya ke Ange dan Stan, dan untuk menunjukkan hal ini, ia meraih teleponnya; foto-foto terbarunya menggambarkan mereka semua berdiri bersama, tersenyum.
Namun ayahku menyela.
“Jangan,” katanya. “Kita akan menghapus foto-foto itu. Aku hanya berpikir sebaiknya kita simpan saja kalau-kalau polisi membutuhkannya.” Ada kecanggungan, keheningan, lalu ibuku menyimpan telepon genggamnya. Akhirnya, foto-foto itu dihapus.
Pada kesempatan lain, setelah hari pertama persidangan, ketika kami kembali ke akomodasi, paman saya mengungkapkan kegelisahannya melihat terdakwa.
“Saya tidak percaya itu dia. Rasanya seperti kita mengenalnya dan tidak mengenalnya di saat yang bersamaan. Sulit untuk menyebutkan namanya, dan aneh mendengar pengadilan berganti-ganti antara memanggilnya dengan nama dan memanggilnya ‘terdakwa’. Rasanya seperti saya tidak tahu harus memanggilnya apa.”
“Jangan panggil dia dengan sebutan apa pun,” kata Ayah.
Apa artinya menghapus identitas orang yang masih hidup dengan cara-cara ini? Pembungkaman seperti itu kontras dengan upaya identifikasi yang dilakukan atas nama Ange sebagaimana dijelaskan di atas. Mengakui hubungan kita dengan pembunuh Ange terlalu sulit, sebagian karena hal itu menunjukkan bahwa kita dapat meramalkan tanda-tandanya dan mencegah kematiannya. Namun tentu saja, itu adalah pemikiran yang tidak berdaya. Sebaliknya, dengan merendahkan martabat terdakwa, dengan menghapus identitas pembunuhnya, kita menghapus hubungan pribadi kita dengannya. Keheningan menjadi perantara makna. Ia menegaskan apa yang dapat dan tidak dapat dikatakan ketika menceritakan hal-hal yang rumit dan menghadirkan kesedihan. Memanusiakan kembali orang yang telah meninggal bergantung pada kemampuan untuk memulangkan identitas mereka dari keterlibatannya sebagai subjek pembunuhan. Pemulangan seperti itu, meskipun berhasil, tidaklah sempurna. Karena hal itu hanyalah penindasan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh pembunuh dan pembunuh atas identitas orang yang terbunuh. Dalam keadaan seperti ini, memilih untuk tidak menceritakan atau menceritakan kembali aspek-aspek tertentu dari kematian Ange menjadi mekanisme tersendiri untuk menegaskan kembali kendali atas kekacauan ketidakpastian. Atribusi ketidakberartian dan ketidakberartian adalah negasi. Negasi dapat berupa substitusi—istilah yang dinegasikan diganti dengan yang baru—atau dapat menciptakan tanda indeks ketidakhadiran, di mana penghilangan makna memberikan bentuk maknanya sendiri pada peristiwa, menekan beberapa jenis narasi, sementara membiarkan yang lain berkembang.
Cara kita menceritakan sebuah peristiwa memformalkan pilihan representasional yang kita gunakan untuk menggambarkan pengalaman dan hubungan kita dengan sebuah peristiwa. Jadi, “membuat tidak masuk akal” adalah bentuk pembuatan makna tersendiri. Saya menyatakan bahwa rendahnya kemampuan bercerita bukan hanya keengganan untuk bercerita atau keengganan yang dirasakan untuk mendengarkan, tetapi juga dapat muncul dari keengganan untuk membuat sesuatu masuk akal . Jika memorialisasi bergantung pada pembuatan jenis ikon dan indeks tertentu, maka sebagai perluasan, hal itu memerlukan penolakan atau penekanan atau, seperti yang menjadi pokok bahasan bagian berikut, transformasi yang lain.
Mengubah bahasa kekerasan
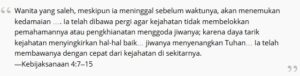
Upacara pemakaman Ange diadakan di gereja Katolik. Prasasti Alkitab di atas dipilih untuk upacara requiem. Dijelaskan oleh Snow dkk. ( 1986 ) sebagai “jembatan bingkai”, teks Alkitab diposisikan secara analogis dan harfiah (yaitu, di halaman, di dalam buku pemakaman, di samping gambar Ange) dengan narasi kematian Ange.
Keluarga saya berdebat tentang cara mengungkap penyebab kematian yang tidak wajar. Ada kekhawatiran apakah kami harus membahas kekerasannya, atau jika dengan melakukannya, kami akan secara tidak sengaja mengalihkan fokus dari Ange ke aspek sensasional kematiannya. Kami berkonsultasi dengan pendeta setempat. Pendapatnya adalah bahwa kami dapat menyinggung tentang kematian yang tidak wajar secara tidak langsung, secara kiasan.
“Kami tidak ingin membicarakan apa yang terjadi,” kata saudara laki-laki Ange. “Kami tidak ingin menyebutkan namanya atau… Saya tidak bisa mengatakan apa pun tentang detailnya. Itu harus tentang dia, tentang mengingat siapa dia. Saya rasa saya tidak akan bisa melewatinya jika tidak demikian.”
Pidato penghormatan terakhir itu merupakan usaha bersama saudara-saudara laki-laki dan anak-anak laki-laki Ange. Setiap penyebutan tentang kematiannya disampaikan dengan cara yang halus; semua pembicara menyebut Ange sebagai orang yang “diambil” dari kami. Ketidakwarasan kematiannya tidak boleh dibiarkan mengaburkan makna hidupnya. Sebaliknya, tidak memberikan penghormatan kepada cara kematian yang tidak wajar berarti melakukan ketidakadilan lebih lanjut. Dalam homili pendeta, ia menguraikan tentang perlunya menghadapi kekerasan sebagai fakta sejarah manusia. Meskipun salinan homili tidak tersedia, dalam jurnal saya dari hari itu saya ingat bagaimana

Ange telah “diambil” dari kami, dan kami sekarang terlibat dalam mediasi ritual atas kehilangan itu ke dalam narasi baru: tentang “persidangan” eksistensial yang penuh dengan ancaman “kemenangan” dan “kekalahan.” Bahasa persidangan dalam Alkitab bertepatan dengan persidangan hukum, tetapi medan yang sudah dikenal dari persidangan pertama bagi keluarga Katolik saya memberikan penghiburan, seolah-olah pertempuran hukum kami yang akan datang dapat dibingkai bersama dengan cobaan berat para Leluhur.
Yang mungkin lebih penting adalah rujukan kepada paradoks Kristus dalam homili Bapa. Dalam teologi Katolik, Yesus mewakili rekonsiliasi paradoks; Gereja mengakui, misalnya, bahwa Kristus sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, baik kekal maupun temporal. Bagi Kierkegaard ( 1946 , hlm. 35–37), ini adalah “paradoks absolut.” Kita tidak dapat memahami Tuhan karena Tuhan pada dasarnya berbeda dari manusia. Perbedaan ini menantang kita untuk merenungkan bagaimana yang dapat diketahui diterangi dengan mengontraskannya dengan Esensi yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui ini. Dalam hubungan yang sama, kematian Ange mampu merujuk kita kembali ke kehidupan. Bacaan dari Kebijaksanaan tidak menawarkan penjelasan tentang kematian, tetapi sebaliknya mengingatkan kita bahwa “dia meninggal sebelum waktunya….” Itu lebih dari sekadar menjembatani kerangka. Sebaliknya, kita diberi logika di mana dimungkinkan untuk secara bersamaan memahami kematian yang tidak masuk akal di dunia yang sebaliknya masuk akal.
Para peneliti yang bekerja dengan korban pembunuhan telah menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas dapat membantu pemulihan psikologis (Mastrocinque et al., 2020 ; Wellman, 2014 ; Armour & Umbreit, 2012 ; Engel, 1977 ). Pendapat saya adalah bahwa agama menawarkan keluarga saya kesempatan untuk mengontekstualisasikan kembali fakta-fakta pembunuhan yang penuh kekerasan dengan cara yang tampak lebih “dapat diceritakan.” Dengan mengubah atau menyalin pembunuhan ke dalam kerangka linguistik baru—salah satu metafora—kita dapat lebih mudah mengucapkan apa yang mungkin akan membebani kapasitas kita untuk menceritakannya.
Dua tahun sebelum duduk di pengadilan sambil menunggu putusan, saya sedang dalam perjalanan pulang bersama seorang teman lama sekolah. Saat itu adalah Hari Tahun Baru. Kami baru saja merayakannya di Sydney.
Kami berhenti untuk mengisi bensin di sebuah kota pertambangan batu bara tua di kaki Blue Mountains. Saya melangkah keluar ke udara yang panasnya 40°C dan menyalakan ponsel saya. Ada kabut tebal di udara; Central West telah diselimuti kebakaran hutan selama berminggu-minggu, dan lanskapnya hancur, tandus, dan tembus pandang.
Banjir panggilan tak terjawab dan pesan teks bermunculan. Saat itu adalah Malam Tahun Baru, dan hal-hal seperti itu sudah bisa diduga .
“Saat itu malam Tahun Baru, dan hal-hal seperti itu sudah bisa diduga,” kata pengacara pembela.
Detektif Owen mencondongkan tubuhnya ke mikrofon dengan tidak nyaman. Dia telah berada di mimbar selama lebih dari 2 jam. “Tentu saja,” jawabnya.
“Dan apakah Anda berbicara dengan penghuni kompleks lainnya?”
“Kami berbicara dengan sejumlah besar warga. Ada laporan tentang kebisingan malam itu sekitar pukul 10.30 malam, yang sesuai dengan rekaman CCTV yang kami temukan.”
“Tetapi Anda pasti setuju, bukan, bahwa, karena saat itu adalah Malam Tahun Baru, suara-suara seperti… teriakan dan, jika menggunakan bahasa sehari-hari, ‘berjalan terus,’ bisa saja terdengar?”
“Ya. Dan mereka yang kami ajak bicara tidak dapat mengatakan apakah itu teriakan—semacam perayaan—atau apakah itu suara sesuatu yang lebih menyeramkan.”
Analogi yang saya ambil dari gagasan Marx bahwa sejarah terjadi dua kali, pertama sebagai tragedi, lalu sebagai lelucon—dalam hal ini, lelucon proses hukum—menyembunyikan cara narasi selalu mengartikulasikan realitas sebagai sesuatu yang dipahami. Genre hukum yang menjadi dasar transformasi narasi keluarga saya hanyalah pengulangan lain dari hal yang sama, sementara masalah yang dihadapi tidak berubah: bagaimana menanggung hal terburuk yang ditawarkan kehidupan, tanpa membiarkan diri dikalahkan dalam prosesnya.
Suatu sore selama persidangan, kami berkendara ke rumah Ange dengan makna baru yang terukir di kepala kami untuk diproyeksikan ke tempat itu. Di sinilah kartu-kartu banknya disembunyikan, tempat blok pisau tergeletak, dan tempat ia ditemukan oleh responden pertama.
Pemulihan diri secara virtual yang dijelaskan sebelumnya selalu dikepung oleh penindasan virtual yang dilancarkan oleh adegan-adegan tersebut terhadap ingatan, orang, dan tempat. Mungkin pemulihan diri bukanlah tindakan emansipatoris, seperti yang dikemukakan Martin, tetapi tindakan penyeimbangan. Para korban bersama terjebak dalam situasi yang tidak seimbang antara kebutuhan yang tidak sepadan. Keengganan alami terhadap informasi traumatis bertentangan dengan keterlibatan yang diperlukan dalam proses peradilan pidana. Memanusiakan kembali orang yang telah meninggal bergantung pada berbagai bentuk karya naratif. Yang paling penting menurut pengalaman saya, ikonisitas daging, yang dipermalukan oleh kematian yang kejam, harus dilepaskan.
“Itu bukan dia,” kata Ibu di rumah duka. “Dia sudah tiada dan yang ada di sana bukanlah dia.” Narasi kita tentang siapa Ange berjuang untuk mendapatkan legitimasi melawan ketidakpastian penyelidikan dan narasi pengadilan yang saling bertentangan, yang semuanya berujung pada dilema lain: untuk mencapai keadilan bagi orang yang dilecehkan berarti menanggung pelanggaran lebih lanjut.
BAGIAN II: SIDANG
Masa kini yang temporal hanya memiliki hubungan samar dengan masa depan. Itulah yang disebut Kermode ( 1968 , hlm. 140) sebagai “bagian tengah yang tidak berkesinambungan dan tidak terorganisir.” Di pengadilan, mudah untuk melihat bagaimana makna bagian tengah ini bergantung pada hubungannya dengan putusan di masa mendatang. Apa yang “dimaksud” oleh suatu argumen tertentu terletak pada pengaruh fungsionalnya terhadap putusan atau hukuman.
Kami telah melakukan perjalanan ke Wollongong di tengah ketidakpastian. Dengan munculnya kembali kasus COVID-19, pengadilan menjadi kacau balau. Setelah juri dibentuk, jaksa penuntut berhasil meminta keringanan hukuman dari hakim untuk mengizinkan kami menghadiri persidangan secara langsung. Hingga saat itu, kami berenam duduk di ruang tamu sebuah rumah yang disediakan oleh Kelompok Dukungan Korban Pembunuhan. Kami minum kopi dan mengutak-atik tautan video yang menghubungkan kami ke pengadilan. Ada perasaan jengkel—bahwa kami dihapus dari mise-en-scene .
Pastikan kami diberitahu bahwa video dan mikrofon Anda dimatikan .
Dengan cara ini, kami mendengarkan ringkasan pembukaan dari jaksa penuntut dan pembela, terdiam karena kebrutalan kematian Ange melampaui imajinasi kami sendiri. Ia menderita luka tusuk mulai dari wajah hingga pusar . Kami akan mendengarkan kesaksian ahli, jaksa penuntut dengan tegas menyatakan, yang menggambarkan kedalaman dan dampak luka-luka tersebut; kami akan mendengar suara almarhum melalui rekaman CCTV pada malam itu; kami akan mengikuti pergerakan pasangan itu sepanjang hari yang biasa-biasa saja hingga ke kejadian-kejadian yang tak terduga pada malam itu.
Di pengadilan, realitas pembunuhan yang kompleks dimediasi melalui “fakta” yang bersifat pembuktian, yang maknanya diperdebatkan oleh pengacara, yang mengontekstualisasikannya sedemikian rupa untuk memungkinkan atau menantang penuntutan. Objek dikontekstualisasikan kembali sebagai “bukti,” dan pengacara mengilhami mereka dengan pentingnya; korban manusia dari pembunuhan ditransposisikan ke dalam status korban Persemakmuran (Freiberg, 1988 ). Seorang jaksa penuntut umum ditunjuk dan transkrip proses pengadilan dibuat dalam tindakan entekstualisasi prototipe.
Entekstualisasi memusatkan kembali wacana dalam kerangka kontekstual yang baru. Makna tindakan ini bagi argumen saya terletak pada perbedaan yang jelas: bahwa apa yang secara hukum penting bagi pengadilan, dan apa yang secara pribadi penting bagi para korban, adalah dua hal yang sangat berbeda.
Ketika keluarga saya mencari jawaban untuk mengapa , praktisi hukum malah bertanya siapa , dan sebagai konsekuensinya, bagaimana . Dengan kata lain, apa yang secara naratif memadai bagi hukum mungkin tidak selaras dengan kecukupan naratif para korban. Sering kali, saya dibiarkan bingung mengapa fakta-fakta tertentu ditekankan sementara yang lain—yang tampaknya berharga—hampir tidak disebutkan. Akar dari ketidakselarasan ini adalah kurangnya keahlian, ketidakmampuan untuk “membaca” signifikansi hukum dari tanda-tanda tertentu, yang merupakan hasil dari kemiripan dengan preseden. Aturan ini dikenal sebagai stare decisis . Seperti yang ditulis Jerome Bruner ( 1991 , hlm. 18), “sejauh hukum bersikeras pada perolehan kasus seperti itu sebagai ‘preseden,’ dan sejauh ‘kasus’ adalah narasi, sistem hukum memaksakan proses perolehan narasi yang teratur.” Pejabat hukum membandingkan kasus-kasus masa lalu dengan masa kini, menyusun otoritas kasus mereka dengan menjawab pertanyaan: “atas otoritas apa bukti X menjadi pembelaan yang baik, atau fakta penuntutan?” Toulmin ( 1958 , hlm. 98–99) menggunakan istilah “warrant” untuk menggambarkan bentuk argumentasi ini, di mana relevansi fakta-fakta tertentu bergantung pada kumpulan pengetahuan tertentu (seperti preseden). Stare decisis merepresentasikan apa yang disebut Silverstein ( 1993 ) sebagai struktur metapragmatik, karena pengacara mencoba menunjukkan karakter arketipe tertentu pada kasus saat ini. Arketipe ini mengarahkan alur argumen pengacara atau hukuman hakim (Mertz, 2007 , hlm. 58). Narasi dibangun dari dan untuk perbandingan. Dengan demikian, profesional hukum terlibat dalam siklus referensi-diri yang mendefinisikan praksis dan tradisinya (Bruner, 1991 , hlm. 18). Bukti x menjadi bermakna karena dapat dibangun sebagai indeks preseden , yang memungkinkan kita untuk menanyakan efek apa yang ditimbulkan oleh interaksi melingkar antara ahli hukum—bukti—preseden terhadap pembacaan peristiwa oleh orang yang bukan ahli.
Membangun makna: Karakter dan preseden
Biasanya, sebagai orang yang bukan ahli hukum, para korban bersama tidak dapat memanfaatkan kumpulan metapragmatik preseden hukum. Mereka tidak dapat membuat hubungan indeksikal dengan cara yang sama seperti para ahli hukum. Dengan tidak adanya keahlian hukum, para korban bersama membangun narasi yang mengindeks peristiwa dengan cara yang berbeda, meskipun paralel, saat mereka mengartikulasikan kesadaran hukum mereka sendiri. Misalnya, para korban bersama memanfaatkan kumpulan ingatan ahli mereka yang unik untuk menantang klaim yang dibuat di pengadilan. Seharusnya mungkin untuk mengamati bagaimana narasi yang bersaing menjelaskan fakta yang sama dengan cara yang berbeda, yang diambil dari kumpulan preseden yang berbeda. Misalnya, ibu saya menceritakan bagaimana:

Yang penting, potongan di atas mata terdakwa itulah indeks yang relevan. Bagi pembela, potongan ini dibacakan dalam narasi di mana Ange menyerang pembunuhnya. Bagi keluarga saya dan jaksa penuntut, potongan ini “dibacakan” sebagai pembelaan diri Ange. Demikian pula, saya memperkenalkan contoh kedua, menyimpan analisis panjang saya hingga setelah entri jurnal pribadi saya, yang dilengkapi dengan koda retrospektif yang ditulis 2 minggu setelah kejadian.
13.1.22
Pihak pembela [memeriksa] ahli patologi forensik [yang memeriksa luka Ange] .
Pembela berulang kali bertanya tentang luka di tangan Ange: “Mungkin saja,” katanya/bertanya, “luka/memar seperti itu bisa jadi akibat korban menyerang terdakwa, bukan?”
Ahli patologi mengakui bahwa, meskipun mungkin, luka-luka tersebut lebih konsisten dengan luka pertahanan diri: lengan atau tangan terangkat untuk menahan pukulan, bukannya untuk menyerang.
“Tetapi Anda mengakui bahwa ada kemungkinan hal itu disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal?”
“Mungkin saja, tapi menurut perkiraanku itu bukan kasusnya.”
Analis DNA mendeteksi sebagian kecil darah terdakwa tercampur dengan darah Ange dalam usapan yang diambil dari mulutnya .
Pihak pembela mencoba menafsirkan hal ini dengan maksud bahwa Ange telah menggigit terdakwa, memasukkannya ke dalam ceritanya yang menggambarkan Ange sebagai penyerang .
Analis DNA menunjukkan bahwa Ange ditikam di wajah dan sampel darah campuran sudah diduga, mengingat tangan terdakwa terluka dan darahnya ditemukan pada setiap senjata .
Koda
Pihak pembela menginterogasi ahli patologi mengenai penyebab kematian, dengan menyatakan bahwa itu adalah kehilangan darah secara bertahap , yang menunjukkan gambaran “kehilangan” kehidupan secara perlahan dan tanpa kekerasan .
Dokter patologi tidak setuju. Setelah dia ditusuk di katup aorta, terjadi kehilangan banyak darah .
“Tergantung bagaimana Anda mendefinisikannya secara bertahap,” kata ahli patologi. “Namun setelah luka di jantung, kematian akan terjadi dalam waktu tiga puluh detik.”
Ini mengakhiri pemeriksaan silang pembelaan .
Alur pertanyaan bermunculan, mengendap menjadi narasi yang mungkin (baik implisit maupun eksplisit). Dalam contoh di atas, ibu saya dan saya menantang interpretasi “goresan” di atas mata terdakwa yang disampaikan oleh pembela. Dalam contoh kedua, pemeriksaan silang pembela terhadap ahli patologi forensik berakhir tiba-tiba setelah ia menjelaskan penyebab kematiannya. Itu bukanlah eskalasi kekerasan yang bertahap dan saling balas; itu bukanlah saling balas. Hal penting dalam kesaksian terdakwa adalah pengakuannya bahwa Ange tidak menyerangnya, juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya secara historis—pembenaran atas keahlian pribadi kami seputar karakter Ange.
Dalam entri jurnal di atas, ahli patologi forensik pertama kali menggunakan istilah ‘bertahap’ dalam kaitannya dengan kematian Ange, tetapi mengubah istilahnya setelah pembela menafsirkannya secara tidak terduga. Mereka berdebat secara semantik tentang kata tersebut karena kata tersebut memberikan cerita tertentu tentang menit-menit terakhir Ange. Dari sudut pandang pembela, kematian bertahap memberikan kemungkinan bahwa terdakwa tidak bermaksud membunuh Ange. Sengaja menyakiti orang lain tanpa niat membunuh dapat menjadi pembeda antara dakwaan pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja . Sebaliknya, kematian mendadak di tengah-tengah penyerangan yang kejam membuatnya tampak seolah-olah terdakwa menyerang sampai mati , dan dengan niat yang jelas untuk mengakhiri hidupnya. Pada skala ini, sebuah drama tentang konstruksi leksikal kematian Ange terjadi di mana pilihan “komposisi” memengaruhi definisi hukum yang menjadikannya berubah menjadi “almarhum.” Namun, ini adalah skala pemahaman yang secara kualitatif berbeda dengan keluarga saya, karena skala ini mengembangkan dan mendefinisikan hubungan kausal tanpa harus menawarkan alasan berskala lebih besar untuk pembunuhan tersebut sejak awal. Dimungkinkan untuk membuat kesimpulan panjang yang menggabungkan dan mencakup banyak atau semua “fakta” hukum, namun tetap menghindari pertanyaan tentang mengapa rangkaian peristiwa ini pertama kali dimulai. Meskipun “ketiadaan motif” menawarkan bentuk maknanya sendiri—secara naratif (tidak untuk berbicara tentang eksistensi ) hal itu tidak memuaskan, mengarungi ambiguitas.
Bagaimana para korban bersama bergulat dengan teks-teks hukum yang tidak memuaskan ini dibahas di bagian berikut, di mana saya terus meneliti kerja intertekstual dan internarasi yang rumit yang dilakukan oleh keluarga saya selama persidangan. Pekerjaan ini dicirikan oleh kesadaran hukum kita yang terus berkembang dan berguna dalam mengilustrasikan bagaimana narasi para korban bersama berjuang untuk memulihkan rasa makna hidup dalam konteks pembunuhan tanpa motif dan pada skala apa makna ini diutarakan.
Arti Sebuah Cerita
Pilihan komposisi seperti struktur narasi berdampak signifikan pada pemahaman kita tentang bagaimana sebuah peristiwa dientekstualisasikan. Subjek atau objek tertentu x menjadi bermakna melalui komposisi naratifnya, karena berorientasi dalam hubungan kausal dengan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, terlepas dari apakah korelasi ini sudah ada sebelum proses narativisasi. Tetapi hubungan ini adalah kesalahan post hoc ergo propter hoc , yang diuraikan oleh Roland Barthes ( 1975 , hlm. 248), di mana, karena y mengikuti x , x diasumsikan sebagai penyebab y . Terlepas dari mekanisme kausal yang “alami”, dalam menarasikan, kita mengambil alih sebab-sebab karena sebab-sebab tersebut memberikan logika yang diinginkan.
Narasi berikut ini mencakup beberapa perampasan semacam itu, yang analisisnya akan dibahas di sisa artikel ini, jadi saya menyajikannya di sini secara lengkap. Narasi ini diambil dari suatu malam menjelang akhir persidangan, saat orang tua saya, paman saya, putra-putra Ange, dan saya berdiskusi di ruang tamu akomodasi kami. 5
Di atas adalah cerita bersama tentang berbagai peristiwa di mana kesaksian terdakwa diceritakan sebagian, dan prediksi tentang hasil persidangan dibahas. Kata-kata terdakwa dikutip secara langsung (misalnya, baris 1, 7, 11) dan dilaporkan secara tidak langsung (misalnya, baris 14). Sementara percakapan berlanjut setelah pertukaran ini, percakapan tersebut berubah arah, berputar di baris 46–48 untuk memulai sebuah koda.
Proyek naratif di atas memiliki beberapa fitur yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah kiasan terhadap jenis narasi yang sangat berbeda, yaitu narasi tentang anak kecil, saat si pembunuh diejek sebagai “seperti anak kecil, yang hanya berkata ‘lalu lalu lalu lalu’.” Yang lain adalah saran tentang karakter, dan narasi irrealis yang dikemukakan Thomas: Jika seseorang adalah tipe orang yang akan menikam seseorang di wajah dan leher, tipe orang seperti itu tidak akan pernah dengan tulus mengatakan bahwa mereka “hanya mencoba menyakiti mereka” daripada membunuh mereka. Mungkin, fitur yang paling penting adalah diskusi dan integrasi fraseologi hukum yang jelas. Kami mengadopsi eponim “terdakwa,” memperdebatkan sifat “keraguan yang wajar,” dan berdebat tentang makna dan signifikansi “cedera tubuh yang parah” terhadap hasil persidangan.
Saya kurang tertarik pada makna-makna rakyat yang kita kaitkan dengan ide-ide ini daripada dengan memahami signifikansi naratif istilah-istilah ini dalam wacana kita. Dapat dikatakan, dalam diskusi di atas, tidak ada konsensus yang dicapai tentang arti dari “keraguan yang wajar” atau “cedera tubuh yang parah,” namun istilah-istilah ini mengeras menjadi definisi yang diasumsikan. Mereka menjadi objek akal sehat yang lebih tinggi (Amsterdam & Bruner, 2000 , hlm. 135). Terlepas dari kelemahan definisi ini, perdebatan berakhir untuk saat ini, dan istilah-istilah tersebut digunakan sebagai objek makna yang stabil secara fungsional. Kita mengimpor fraseologi hukum ke dalam ucapan kita sendiri sebagai artefak wacana ruang sidang, dan “menaturalisasikannya” dalam wacana kita sendiri; mereka tertanam kembali secara tekstual. Jenis karya naratif ini juga disebut sebagai “interdiskursivitas,” karena gaya linguistik dicampur (Bhatia, 2010 ).
Memahami istilah-istilah ahli hanya menjelaskan sebagian fenomena tersebut. Yang lebih menarik adalah konsekuensi dari interdiskursivitas kita terhadap narasi kita—untuk tujuan apa kita mengintegrasikan bahasa ahli dalam teks kita? Jawaban awal adalah bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut mencerminkan perluasan kesadaran hukum masing-masing pembicara. Selangkah lebih jauh dan saya berhipotesis bahwa ekspresi kesadaran hukum ini menyusun otoritas teks-teks kita. Peristiwa interdiskursif menjadi pernyataan epistemologis, karena proses hukum ditafsirkan, direplikasi, dan dicantumkan kembali dalam peristiwa tutur non-ahli. Penggunaannya menegaskan otoritas pembicara, karena pepatah tersebut merupakan klaim untuk mengetahui—terlepas dari penggunaan yang benar secara hukum. Namun, penggunaan yang benar adalah kepentingan sekunder untuk penggunaan yang meyakinkan , karena kualifikasi sebuah cerita bergantung pada kapasitasnya untuk meyakinkan audiensnya: itu harus tampak benar. Ini adalah prinsip verisimilitude, bukan verifiability. Seperti yang ditulis Jerome Bruner ( 1991 , hal. 9), “pendongeng hebat menguasai dengan baik tipu daya konstruksi realitas naratif sehingga cerita mereka mendahului kemungkinan interpretasi apa pun kecuali satu interpretasi….”
Kita dapat menganggap perdebatan keluarga saya tentang, dan penggunaan, terminologi hukum sebagai inklusi gaya dasar, yang menunjukkan (atau memberikan ilusi) keakraban pembicara dengan paradigma hukum. Dunia tampak dapat diketahui: memang, meskipun hanya sementara, dunia tampak diketahui . Entekstualisasi interdiskursif berfungsi seolah-olah, dalam kata-kata Hölderlin, “Rekonsiliasi terjadi di tengah pertikaian, dan segala sesuatu yang terpisah menemukan dirinya kembali” (dalam Forbes, 1980 , hlm. xi).
Untuk menegaskan kembali, jika penggunaan bahasa teknis hukum dalam kisah-kisah pribadi kita merupakan sebuah klaim untuk memahami bahasa tersebut, maka klaim untuk memahami bahasa tersebut juga berfungsi secara otoritatif: klaim ini merupakan salah satu indikasi hak prerogatif pencerita untuk menceritakan kisah ini .
Bernstein ( 1994 , hlm. 7) dan Morson ( 1994 , hlm. 3) telah menggambarkan sebuah mode aktivitas naratif yang mereka sebut “sideshadowing.” Sideshadowing terjadi ketika pencerita menyarankan atau menguraikan narasi yang berbeda, hipotetis, dan paralel dengan narasi mereka sendiri. Ini dapat dianggap sebagai jenis entekstualisasi lain, di mana diskusi tentang masa kini dilemparkan, atau diproyeksikan, atau dilemparkan ke dalam wacana irrealis. Sebuah cerita tentang bahasa tubuh juri mungkin menghasilkan teks paralel tentang keadaan emosional mereka, pendapat mereka terhadap kesaksian terdakwa, dan sebuah vonis.
Dengan cara yang sama, ketidakbersalahan atau kesalahan terdakwa dipertimbangkan secara bersamaan, tidak satu pun (pada awalnya) melarang yang lain. Namun, ini adalah jenis sideshadowing tertentu, yang membangun logika penjelasan yang mengarah ke makna yang berbeda atau dibingkai secara berbeda dari yang ada di ruang sidang. Saat kita menceritakan bersama peristiwa-peristiwa persidangan, kita juga berhipotesis tentang kemungkinan konsekuensinya. Kembali ke penceritaan di atas, pada baris 1–2, 12–16, dan 31–32, kita mengurangi pengalaman kita di pengadilan untuk merasionalisasi tentang kemungkinan hasil. Skeptisisme Ben yang jelas bekerja dalam dialog dengan hipotesis Thomas dan Ruth. Bolak-balik ini menghasilkan sesuatu yang mendekati penalaran deduktif. Kemungkinan keraguan yang wajar diduga (baris 19–21, 39–41), hanya untuk “dibantah” berdasarkan hipotesis yang lebih tegas (baris 30–36, 38–40). 7
Seperti yang diuraikan Amsterdam dan Bruner, narasi dapat dianggap sebagai pemodelan realitas, dan dengan demikian, “mewakili kemungkinan cara di mana peristiwa-peristiwa di dunia manusia dapat terjadi” ( 2000 , hlm. 133). Pekerjaan interdiskursif dari anggota keluarga saya membantu dalam penciptaan teks-teks dengan cincin kebenaran. Semakin mudah pencerita menavigasi dan mengintegrasikan bahasa pengadilan, semakin meyakinkan narasi mereka, memberikan kesan pemahaman. Akibatnya, pencerita seperti itu dapat lebih baik (yang saya maksud lebih meyakinkan) menyampaikan prediksi mereka tentang masa depan. Dengan kata lain, mereka lebih efektif memahami keadaan saat ini, dan lebih kredibel menafsirkan hasil masa depan.
Untuk tujuan ini, pemaknaan bersama korban tidak harus bertentangan dengan perasaan tidak masuk akal. Kita tidak selalu berusaha untuk memaknai ketidakberartian, tetapi mengintegrasikannya dalam pandangan dunia yang menempatkan kurangnya makna ini dalam narasi yang lebih luas.
Skala pembuatan makna
Pembuatan makna melibatkan abstraksi, yang melaluinya narator secara selektif memaknai pengalaman mereka. Alasan mereka untuk bersikap selektif tidak selalu karena sifat sulit dalam mengomunikasikan hal-hal traumatis. Sering kali, hal itu hanya karena alasan waktu atau kenyamanan. Namun dalam kasus kekerasan yang rasa sakitnya menguasai naratornya, selektivitas penceritaannya menunjuk pada kekuatan dan makna dari keheningannya. Keheningan menjadi signifikan, relasional. Namun untuk melihatnya, konteks di mana cerita terbentuk menjadi sangat penting, kritis untuk memahami apa yang dipahami oleh pencerita, dan bagaimana mereka melakukannya. Pembuatan makna dalam bentuk naratif lebih dari sekadar deskripsi pengalaman. Itu adalah menceritakan hal-hal yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Namun, itu juga tidak menceritakan hal-hal yang benar dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat, ketika ceritanya adalah salah satu kekerasan yang tidak masuk akal, sebuah cerita yang hanya berdarah dan tidak pernah sembuh. Mereka menjadi objek komposisi kontekstual yang kompleks dan interaktif yang tidak hanya diceritakan tetapi diwujudkan. Sebenarnya, narasi-narasi ini bersaing untuk mendapatkan makna, untuk mendapatkan koherensi duniawi, tetapi sering kali, narasi-narasi itu tidak dan tidak dapat mencapainya. Kita tidak dapat memahami kematian Ange, tetapi kita mengabaikannya, dan mencoba untuk memahami fakta-fakta yang menyertainya. Kita dapat mengaitkan makna pada kehadiran atau tindakan kita sendiri setelah kematiannya, atau hasil persidangan, atau pakaian pemakamannya, atau pemilihan himne pemakaman atau bacaan Alkitab, atau apa pun yang kita pilih untuk diingat tentangnya—dan apa yang kita biarkan terlupakan.
Pertanyaan yang terus-menerus (meskipun sering tidak terucapkan) di antara keluarga saya selama ini adalah: apa yang dapat kami lakukan? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan proses hukum dan proses emosional. Di kemudian hari, pertanyaan tersebut terkait dengan etiologi: “bagaimana hal ini terjadi?” Mengikuti pertanyaan ini, “apa yang dapat kami lakukan untuk meringankan rasa sakit?” Jawabannya tetap sulit dipahami, terikat erat dengan kehidupan yang menghidupkan pengalaman kita, menjalaninya, dan menceritakannya pada saat yang sama. Pengalaman dan narasi bertindak satu sama lain, menciptakan makna dari isinya, dan dengan demikian menjalin apa yang disebut Wittgenstein sebagai bentuk kehidupan. Karena ucapan kita bersifat mengungkap, sekaligus memahami dunia dan memberi makan tindakan kita.
